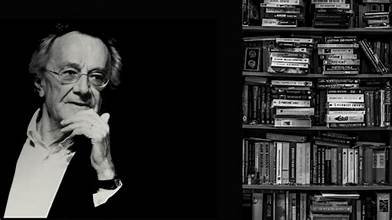PELAKITA.ID – Jean-François Lyotard (1924–1998) adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal sebagai salah satu pemikir utama postmodernisme.
Nama itu mencuat dari seorang senior aktivis Fisip Unhas, Busman Rahman di WAG Alumni Unhas.
Nama Lyotard dia sebut atau kaitkan saat membaca tulisan penulis tentang bagaimana agenda pembangunan yang ambisius namun abai pada kapasitas lokal tersedia.
Siapa Lyotard?
Ia menjadi terkenal lewat karya monumental berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1979), di mana ia melontarkan kritik tajam terhadap apa yang disebutnya sebagai “Grand Narratives” atau “Narasi Besar.”
Bagi Lyotard, narasi-narasi besar telah lama mendominasi cara kita memahami sejarah, pengetahuan, dan kemajuan. Namun, dalam dunia modern yang penuh kompleksitas dan keragaman, ia menilai narasi-narasi besar tersebut telah kehilangan daya legitimasi.
Narasi besar adalah cerita menyeluruh yang mengklaim menjelaskan dunia secara universal—seperti ide bahwa ilmu pengetahuan selalu membawa kemajuan, atau bahwa masyarakat berkembang secara linear dari tradisional ke modern. D
Dalam konteks ini, teori Lyotard bertujuan untuk menggeser fokus dari narasi tunggal menuju “petit récits” atau narasi-narasi kecil: cerita lokal, subjektif, dan beragam yang lebih mencerminkan pengalaman manusia yang sebenarnya.
Lyotard mendorong kita untuk tidak lagi mencari satu kebenaran mutlak, tetapi membuka diri terhadap pluralitas dan keberagaman pengetahuan.
Ia mengajukan bahwa legitimasi ilmu dan kebijakan harus dibangun bukan berdasarkan universalitas, tetapi dari dialog antarrealitas yang berbeda.
Di Indonesia, teori Lyotard menemukan relevansi yang sangat besar. Sejak masa Orde Baru, negara Indonesia dibentuk dan dijalankan dengan pendekatan narasi besar: pembangunan nasional sebagai jalan satu-satunya menuju kemajuan, dengan pusat kekuasaan di Jakarta menjadi penentu utama arah kebijakan dari Sabang hingga Merauke.
Bahkan hingga kini. Tentang pencetakan sawah secara massal, mandiri pangan, mandiri energi, dan lain sebagainya.
Dalam narasi besar ini, semua daerah dianggap seragam, semua masyarakat diasumsikan memiliki kebutuhan yang sama, dan pembangunan dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi dalam kerangka teknokratik.
Namun realitas Indonesia jauh lebih kompleks: terdiri dari ratusan etnis, ribuan pulau, beragam sistem pengetahuan lokal, serta nilai-nilai budaya yang tak bisa diseragamkan.
Teori Lyotard mengajak kita untuk mendengar lebih banyak suara dari pinggiran—suara petani di Moncongloe, perempuan adat di Seko, nelayan teripang di Pulau Satangnga hingga komunitas petani di Tolitoli. Bisa jadi juga tentang kaum perempuan muda yang membangun ekonomi kreatif dari lorong-lorong kota Makassar.
Mereka semua memiliki “narasi kecil” yang justru valid dan penting untuk merangkai masa depan mereka sendiri.
Faktanya, narasi mereka sering terpinggirkan oleh proyek-proyek besar yang tak selalu berpijak pada kebutuhan lokal. Dari proyek food estate, pemindahan ibu kota negara, hingga pembangunan infrastruktur masif, kita sering lupa bertanya: apakah ini kebutuhan mereka, atau ambisi dari narasi besar pembangunan itu sendiri?
Kritik Lyotard juga menyentuh aspek lain: bagaimana kekuasaan dibungkus dalam bentuk pengetahuan.
Dalam konteks Indonesia, ini bisa kita lihat dalam cara negara menyusun kurikulum, membentuk media arus utama, dan menetapkan arah riset universitas—semuanya cenderung top-down dan homogen.
Padahal, pengetahuan lokal seperti sistem irigasi tradisional subak di Bali, hukum adat di Papua, atau manajemen hutan oleh masyarakat Kasepuhan memiliki nilai ekologi dan sosial yang tinggi, namun sering diabaikan karena tak masuk dalam kerangka ilmiah modern.
Lyotard tidak meminta kita menolak pembangunan atau ilmu pengetahuan. Ia mengajak kita untuk lebih reflektif, adil, dan terbuka terhadap keberagaman dalam menyusun arah hidup bersama.
Indonesia hari ini membutuhkan lebih banyak dialog antar-narasi, bukan dominasi satu kebenaran. Kita membutuhkan kebijakan yang lahir dari bawah, bukan sekadar imajinasi pusat.
Pembaca sekalian, negara ini membutuhkan pendidikan yang memberi ruang bagi cara berpikir lokal, bukan hanya meniru standar global dan cenderung memaksa secara halus, cenderung mengikat dalam bentuk narasi loan dan grant.
Begitulah, Jean-François Lyotard memberikan kita alat untuk berpikir ulang tentang kekuasaan, pengetahuan, dan hakikat pertumbuhan dan kemajuan.
Di tangan generasi muda Indonesia, pemikirannya bisa menjadi sumber keberanian baru—untuk membangun bukan hanya secara fisik, tetapi juga membangun makna, identitas, dan keadilan dari akar rumput. Dalam negara yang seluas dan seberagam Indonesia, tak ada satu jalan tunggal menuju masa depan.
Bisa jadi masa depan itu justru terletak pada keberanian mendengar narasi-narasi kecil yang selama ini terabaikan.