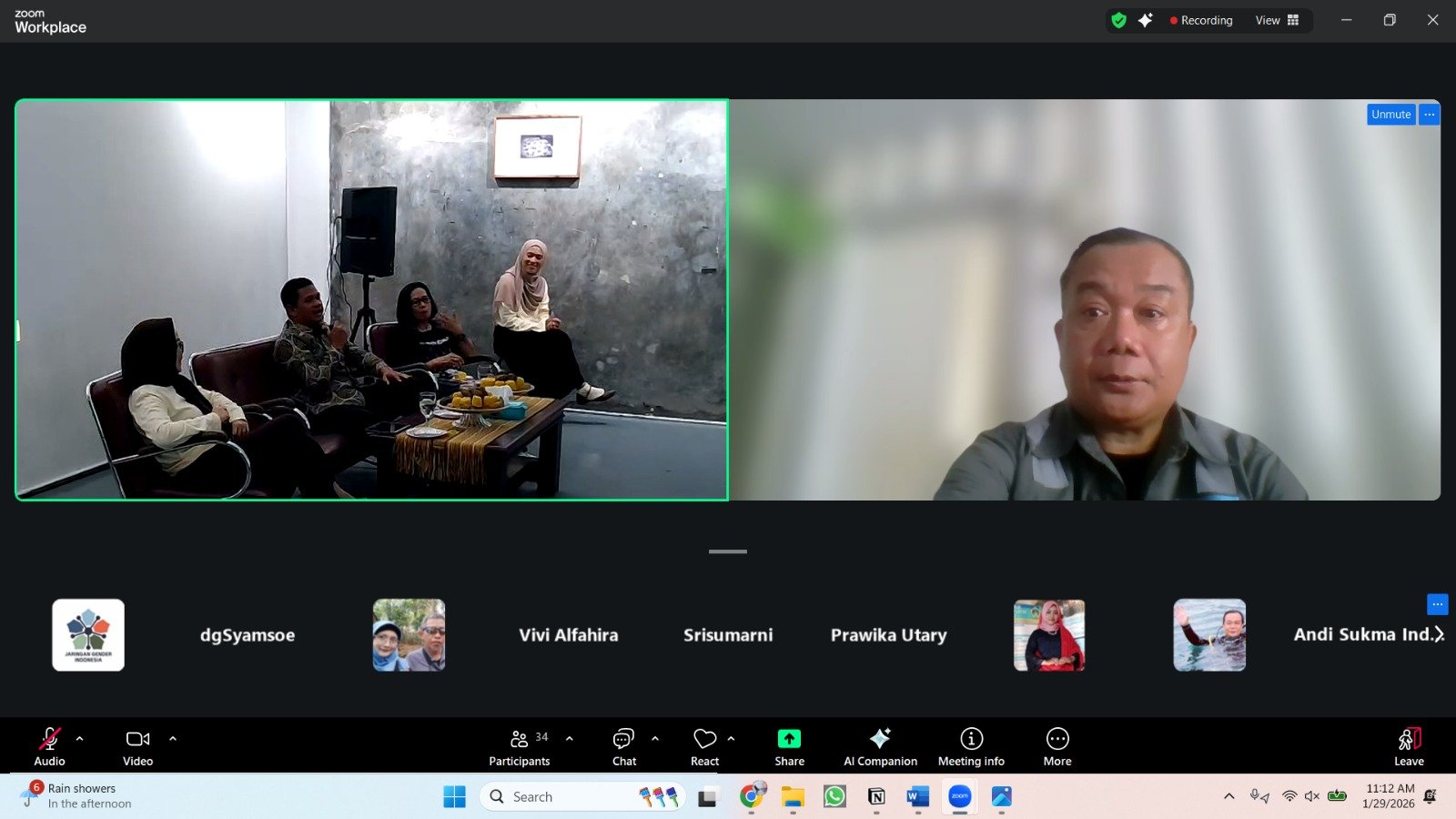Hampir satu dari tiga perempuan berusia 15 tahun ke atas di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Lebih mengkhawatirkan lagi, secara global, satu perempuan dibunuh setiap sepuluh menit.
PELAKITA.ID – Di tengah derasnya arus informasi dan dominasi narasi media arus utama, suara perempuan dan kelompok rentan kerap tenggelam. Padahal, di balik statistik global yang dingin, tersimpan realitas sehari-hari yang menyentuh kehidupan jutaan orang.
Inilah kegelisahan utama yang diangkat dalam paparan bertajuk “Jurnalisme Warga dan Suara Perempuan: Membangun Narasi Melalui Jurnalisme Kritis” yang dibawakan oleh Kamaruddin Azis, pendiri Pelakita.ID, pada 29 Januari di Rumata’ ArtSpace, Makassar.
Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Program Studi Gender dan Pembangunan Universitas Hasanuddin.
Paparan tersebut dibuka dengan data global yang mencengangkan sekaligus menyadarkan.
Hampir satu dari tiga perempuan berusia 15 tahun ke atas di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Lebih mengkhawatirkan lagi, secara global, satu perempuan dibunuh setiap sepuluh menit.
Di era digital yang seharusnya membuka ruang aman berekspresi, kekerasan justru menemukan bentuk baru. Dua dari tiga jurnalis dan aktivis perempuan pernah mengalami kekerasan daring—mulai dari perundungan, ancaman, hingga serangan berbasis gender.
Ironisnya, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan berjalan sangat lambat. Dalam dua dekade terakhir, laju penurunannya hanya sekitar 0,2 persen per tahun.
Angka ini menunjukkan bahwa persoalan ketidakadilan gender bukan semata soal kurangnya regulasi, tetapi juga tentang siapa yang diberi ruang untuk bersuara dan bagaimana cerita-cerita itu dibingkai.
Dalam konteks inilah, jurnalisme warga diposisikan sebagai alat strategis. Menurut Kamaruddin Azis, media arus utama masih memiliki keterbatasan struktural dalam menyediakan ruang yang adil bagi isu gender dan kelompok rentan.
“Banyak pengalaman perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya yang tetap berada di wilayah voiceless—ada, tetapi tidak terdengar,” katanya.
Padahal, masyarakat hari ini hidup dalam kelimpahan gawai dan data. Hampir setiap orang memiliki telepon pintar, akses media sosial, dan kemampuan dasar untuk merekam peristiwa di sekitarnya.
Kondisi ini, jika dikelola secara sadar dan kritis, dapat menjadi kekuatan perubahan sosial. Jurnalisme warga memungkinkan masyarakat menjadi subjek, bukan sekadar objek pemberitaan.
Namun, jurnalisme warga tidak cukup hanya dengan “bercerita”. Di sinilah pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) menjadi penting.
Advokasi berbasis GEDSI menuntut kepekaan terhadap relasi kuasa, etika peliputan, serta keberlanjutan dampak. Suara keadilan gender harus dikelola secara strategis agar tidak berhenti sebagai luapan emosi sesaat, tetapi mampu memengaruhi kebijakan publik.
Paparan tersebut menjelaskan bahwa strategi advokasi perlu dilakukan secara sistematis: dimulai dari pemetaan isu, penguatan basis data dan bukti, pembangunan jejaring dan koalisi, hingga kampanye yang konsisten dan berkelanjutan.
“Jurnalisme warga menjadi pintu masuk untuk mengumpulkan cerita-cerita lapangan yang sering luput dari radar media besar, sekaligus menjadi amunisi advokasi berbasis data dan pengalaman nyata,” jelasnya.
Meski demikian, jalan ini tidak bebas hambatan. Tantangan utama yang disorot adalah minimnya perempuan di posisi pengambil keputusan di industri media dan penyiaran, serta tingginya risiko pelecehan—baik di ruang kerja maupun ruang digital. Selain itu, stereotip dalam pemberitaan masih kuat. Perempuan kerap diposisikan sebagai korban atau pelengkap cerita, jarang dihadirkan sebagai sumber otoritatif yang memiliki pengetahuan dan perspektif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, jurnalisme warga ditawarkan dalam berbagai bentuk yang fleksibel dan kontekstual.
Rilis warga bisa hadir sebagai testimoni, opini komunitas, laporan singkat, video pendek, podcast, hingga unggahan media sosial yang terkurasi.
Salah satu contoh konkret yang dibahas adalah laporan warga mengenai pelayanan publik di Puskesmas yang tidak optimal—sebuah isu sehari-hari yang langsung bersentuhan dengan kehidupan perempuan dan kelompok rentan.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jurnalisme kritis tidak harus selalu megah atau panjang.
“Yang terpenting adalah kejujuran, keberpihakan pada keadilan, dan kesadaran etis dalam menyampaikan cerita,” ucap Kamaruddin.
Di bagian penutup, Kamaruddin menegaskan bahwa suara keadilan gender tidak boleh dibiarkan liar atau terputus-putus. Ia harus dirawat, dipelihara, dan diarahkan secara strategis agar memiliki daya ubah yang nyata.
“Jurnalisme warga, jika dipadukan dengan perspektif GEDSI dan kerja advokasi yang konsisten, dapat menjadi jembatan antara pengalaman sehari-hari masyarakat dengan perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif,” sebutnya.
Di Rumata’ ArtSpace sore itu, diskusi tidak hanya berhenti pada paparan. Ia menjelma menjadi ruang refleksi bersama: tentang siapa yang bersuara, siapa yang didengar, dan bagaimana kita semua bisa ikut menjaga agar narasi keadilan tidak lagi berada di pinggiran.